
Dear all,
Saya baru saja mengikuti Seminar Nasional Sekolah Bertaraf Internasional dengan tema Revitalisasi SBI dalam Rangka Meningkatkan Mutu dan Daya Saing Bangsa yang diadakan oleh Balitbang Kemdiknas pada tanggal 29-31 Oktober 2010 di Grand Zuri Cikarang, Bekasi.
Tak ada yang baru pada seminar tersebut dan yang ada justru semakin kacaunya pemahaman stake-holders tentang program SBI ini. Bahkan Dirjen Mandikdasmen, Prof Suyanto, secara terang-terangan menyatakan bahwa belum ada program SBI (yang ada baru Rintisan) sehingga judul seminar ini justru dipertanyakannya. Sepanjang sesi seminar pejabat dan staf Kemdiknas memberikan kritik dan pertanyaan serius kepada para pemrasaran yang notabene adalah sesama pejabat Kemdiknas! Jika staf Kemdiknas sendiri belum memiliki pemahaman yang sama dan bulat tentang SBI ini padahal program ini telah berjalan selama sekian tahun maka ini jelas merupakan bencana. Studi Evaluasi Penyelenggaraan RSBI/SBI yang dilakukan oleh Pusat Penelitian Kebijakan dan Inovasi Pendidikan (Puslitjaknov) Balitbang dan disampaikan oleh Ir. Hendarman MSc, PhD ternyata hanya mengevaluasi sistem penerimaan peserta, prestasi akademik siswa dan gurunya, sistem pendanaan dan tatakelolanya.
Tak ada evaluasi untuk proses pelaksanaanya di kelas dan apa dampak yang ditimbulkannya. Padahal justru itu yang perlu diteliti.
Hasil studinya justru memperkuat pendapat saya bahwa program RSBI/SBI ini justru akan menurunkan kualitas pendidikan di sekolah yang menyelenggarakannya. Meski simpulannya menyatakan bahwa Siswa RSBI menunjukkan prestasi akademik yang lebih baik daripada siswa regular (Of course of course ! Bukankah mereka memang siswa cream of the cream yang melalui seleksi ketat sebelumnya) tapi ternyata secara rata-rata tidaklah menonjol (hanya lebih tinggi 12% di tingkat SD dan 15% di tingkat SMP). Selain itu ditemukan banyak kasus siswa RSBI/SBI yang justru tidak lulus Ujian Nasional!
Ada dua anggota Komisi X DPR RI yang hadir sebagai pembicara pada acara tersebut, yaitu Dedi Wahidi dan Theresia E.E Pardede (Tere). Dedi Wahidi juga menyampaikan pandangannya yang kritis tentang program ini.
Dari berbagai sekolah yang menyampaikan presentasi bagaimana sekolah (R)SBI ini dijalankan di daerah mereka masing-masing jelas sekali terlihat bahwa terjadi implementasi program yang berbeda antara daerah dan sekolah masing-masing dengan segala interpretasi yang mereka pahami. Bahkan masih banyak daerah yang sekedar melakukan kelas bertaraf internasional di dalam sekolah yang ditunjuk menjadi penyelenggara (R)SBI.
Karena diundang untuk hadir dan juga diminta untuk memberi masukan maka dengan ini saya sampaikan masukan dan usulan saya tentang program ini. Mohon masukannya untuk memperbaiki apa yang saya usulkan disini.
LATAR BELAKANG :
UU Sisdiknas 2003 Pasal 50 ayat (3) dalam yang berbunyi sbb :
3) Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu satuan pendidikan pada semua jenjang pendidikan untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan yang bertaraf internasional.
Istilah satuan pendidikan yang bertaraf internasional itu kemudian diterjemahkan dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 17 tahun 2010 Pasal 1 No 35 menjadi :
Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
Pada PP no 17 tahun 2010 ini frase satuan pendidikan yang bertaraf internasional dalam UU sisdiknas telah berubah menjadi Pendidikan bertaraf internasional dan kemudian dijelaskan dengan tambahan keterangan Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
Pada tahap ini saja telah terjadi penyimpangan definisi di mana pada awalnya pernyataan dalam UU Sisdiknas adalah merujuk kepada sebuah tingkatan keunggulan kualitas yang harus dicapai (yang diberi istilah bertaraf internasional) sedangkan pada PP no 17 tahun 2010 telah berubah makna menjadi sebuah sistem pendidikan yang terpisah dan kemudian berkembang dalam sebuah Peraturan Menteri (Permen 78 Tahun 2009). Sistem ini bertentangan dengan amanat yang ada dalam Sistem Pendidikan Nasional yang dinyatakan dalam pertimbangan sbb :
b. bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;
Definisi yang dimunculkan dalam PP No 17 tahun 2010 ini sendiri tidak jelas acuan, kriteria dan rujukan akademik dan empiriknya. Istilah ini tidak pernah dikenal sebelumnya dan seolah muncul begitu saja dari langit dan berbeda dengan apa yang diamanatkan oleh UU Sisdiknas itu sendiri.
Karena istilah ini tidak memiliki rujukan yang jelas maka istilah ini kemudian diinterpretasikan secara bebas (dan cenderung sembrono) oleh Kemdiknas sehingga menimbulkan berbagai problem dan konsekuensi serius sampai sekarang dan masih belum dapat dipecahkan. Padahal sampai saat ini lebih dari seribu sekolah telah di RSBI-kan. (SD= 195, SMP= 313, SMA=320, SMK=247)
BEBERAPA MASALAH YANG TIMBUL
Karena konsep sekolah bertaraf internasional ini tidak memiliki landasan akademik dan empirik yang memadai, dan hanya berpijak pada landasan hukum, maka konsep dasar yang dirumuskan menimbulkan berbagai masalah yang mendasar. Beberapa diantaranya adalah :
- Penetapan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam mengajarkan beberapa bidang studi menimbulkan banyak masalah dan kontroversi. Kontroversinya adalah bahwa secara empirik ternyata kebijakan ini justru dapat menyebabkan merosotnya nilai dan kompetensi siswa di bidang studi yang diajarkan. Banyak hasil kajian dan juga pengalaman negara Malaysia selama hampir 8 tahun ternyata menunjukkan bahwa penggunaan bahasa Inggris (asing) untuk bidang studi IPA dan MAT justru menurunkan mutu siswa (baca http://ms.wikipedia.org/wiki/Pengajaran_dan_Pembelajaran_Sains_dan_Matematik_dalam_Bahasa_Inggeris). Pengalaman negara Malaysia dengan program pengajaran sains dan matematik di sekolah-sekolah di Malaysia dengan menggunakan bahasa pengantar bhs Inggris[disebut PPSMI] yang telah dimulai sejak tahun 2003 dan akan dihentikan secara total pada 2012 nanti karena dianggap GAGAL. Dari satu hasil riset skala besar yang melibatkan pakar dari sembilan universitas negeri di Malaysia dan lebih dari 15 ribu siswa, PPSMI ini memang tidak menghasilkan apa yang diharapkan pencetusnya. Yang bisa survive hanya sekolah yang berada di kota besar dan sekolah berasrama di kota; pada jenis sekolah lainnya nyaris tanpa ampun terjadi degradasi penurunan mutu. Jadi alih-alih akan meningkatkan mutu pembelajaran Matematika dan IPA yang terjadi justru sebaliknya. Bahkan negara Malaysia yg JAUH LEBIH SIAP secara budaya, infrastruktur, dan SDM dalam menerapkan sistem ini menganggap program ini GAGAL diterapkan dan akan kembali menggunakan bahasa Melayu utk mengajar Sains dan Matematika di sekolah-sekolah mereka. Jadi sungguh salah besar jika kita justru akan mengulangi kesalahan yang dilakukan oleh negara Malaysia.
- Penetapan bahasa Inggris untuk digunakan sebagai bahasa pengantar untuk bidang studi IPA dan Matematika adalah kebijakan yang sembrono dan tidak didasarkan pada studi empiris samasekali. Ide menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dalam pembelajaran juga digunakan secara serampangan dan benar-benar di luar kaidah sehingga justru mengakibatkan kekacauan dan kemerosotan mutu pembelajaran nasional kita. Adalah tidak mungkin kita mengharapkan guru-guru kita untuk menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar dengan kemampuan berbahasa Inggris yang ada. Berdasarkan hasil test TOEIC pada 600 guru dan kepala sekolah RSBI terungkap bahwa 60% dari mereka berada pada level paling rendah kemampuan bahasanya. Mengharapkan guru-guru yang berada pada level terendah kemampuan berbahasa Inggrisnya untuk mengajarkan materi IPA dan Matematika dalam bahasa Inggris adalah kebijakan yang sungguh tidak bertanggungjawab.
- Penggunaan kata atau istilah bertaraf internasional akhirnya menimbulkan banyak program-program yang dipaksakan agar dapat memenuhi kriteria bertaraf internasional tersebut. Penggunaan standar ISO, pengadopsian sistem Cambridge, IBO, Sister School, dll. yang dimaksudkan untuk memberikan justifikasi bertaraf internasional tersebut sebetulnya tidaklah esensial dan sekedar aksesoris dan kosmetik. Hal ini menimbulkan konsekuensi dan resiko di bidang akademik maupun biaya yang mubazir. Salah satunya adalah kesalahan asumsi bahwa Sekolah BERTARAF internasional itu harus diajarkan dalam bhs asing (Inggris khususnya) dengan menggunakan media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD . Padahal negara-negara maju seperti Jepang, Perancis, Finlandia, Jerman, Korea, Italia, dll. yang kita jadikan rujukan tidak perlu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar jika ingin menjadikan sekolah mereka BERTARAF internasional.
- Istilah bertaraf internasional ini kemudian diterjemahkan dan diinterpretasikan secara bebas tanpa kajian dan studi yang layak. Penekanan pada penggunaan piranti media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD juga menyesatkan seolah tanpa itu maka sebuah sekolah tidak bisa bertaraf internasional. Sebagian besar sekolah hebat di luar negeri masih menggunakan kapur dan tidak mensyaratkan media pendidikan mutakhir dan canggih seperti laptop, LCD, dan VCD sebagai prasyarat kualitas pendidikan mereka. Program ini nampaknya lebih mementingkan alat ketimbang proses. Sekolah menafsirkan SBI itu sarananya harus wah, ada lap top, infocus, hotspot, AC, VCD. Padahal pendidikan adalah lebih ke masalah proses ketimbang alat. Internasionalisasi pendidikan dipandang dari segi FASILITASnya dan bukan pada prosesnya.
- Konsep ini kemudian menimbulkan kesalahan asumsi yang mendasar. Kesalahan mendasarnya adalah asumsi dan anggapan bahwa Sekolah Bertaraf Internasional hanyalah bagi siswa yang memiliki standar kecerdasan tertentu. Sekolah yang bertaraf internasional dianggap tidak bisa diterapkan pada siswa yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata. Ini juga mengasumsikan bahwa SNP (Standar Nasional Pendidikan) hanyalah bagi mereka yang memiliki tingkat kecerdasan rata-rata. Ini adalah asumsi yang berbahaya dan secara tidak sadar telah mengkhianati SNP itu sendiri karena menganggap SNP tidak layak bagi siswa-siswa cerdas Indonesia. Lantas untuk apa Standar Nasional Pendidikan jika dianggap belum mampu untuk memberikan kualitas yang setara dengan standar internasional? Ini juga paham yang diskriminatif dan eksklusif dalam pendidikan dan menganggap kecerdasan intelektual yang menonjol merupakan segala-galanya sehingga perlu mendapat perhatian dan fasilitas lebih daripada siswa yang tidak memilikinya. Pendidikan yang berorientasi ke hasil adalah paradigma lama dan telah digantikan oleh pendidikan yang berorientasikan pada proses karena pendidikan itu sendiri adalah sebuah proses.
- Eksperimen kebijakan RSBI ini jelas salah sasaran karena dengan kecemasan yg sama akan kualitas pendidikan yg dianggap merosot pemerintah AS di bawah George Bush kemarin justru mengeluarkan paket NCLB (No Children Left Behind) yg justru menyasar pada siswa-siswa di level terbawah yg diberi penanganan khusus agar tak ada lagi yg tertinggal secara akademik. Dengan mengangkat kualitas siswa paling bawah sehingga tak ada siswa yg ‘left behind’ maka diharapkan akan mengangkat agregat kualitas pendidikan secara makro.
Bandingkan ini dengan program RSBI yg justru ditujukan pada siswa-siswa paling berbakat (cream of the cream) dan diberi perlakuan khusus dengan dana berlimpah padahal mereka secara ekonomi dan akademik sebenarnya lebih mampu dan tidak memerlukan bantuan dibandingkan siswa yg tertinggal. Program RSBI ini malah mengabaikan siswa yg secara ekonomis dan akademis justru membutuhkan penanganan dan biaya. Sesungguhnya program RSBI ini adalah program yg memalukan bangsa dan mengkhianati rakyat kecil. Ingat bahwa ini adalah program pemerintah yg dibiayai oleh pajak dan hutang negara dan bukan program swasta. - Kesalahan asumsi lain adalah bahwa sekolah bertaraf internasional ini haruslah diajar oleh guru-guru yang memiliki gelar S-2 (tanpa memperdulikan kesesuaian dengan bidang studi yang diajarkan di kelas). Ini adalah interpretasi yang tidak memiliki acuan akademik maupun akademik samasekali selain rule of thumb belaka. Kebijakan ini juga bertentangan dengan UU Sisdiknas yang hanya mewajibkan guru untuk memiliki gelar sarjana S-1. Tak ada kajian empirik yang menguatkan kebijakan mengenai guru bergelar master ini dan hanya ditetapkan sekedar untuk menunjukkan eksklusifitas.
- Salah satu alasan yang dikemukakan dalam penyelenggaraan SBI ini adalah untuk mencegah kalangan menengah ke atas untuk mengirim anaknya keluar negeri karena ingin memberikan pendidikan yang bermutu bagi anaknya. Tentu saja alasan ini sangat mengada-ada. Apa ada bukti bahwa dengan adanya program RSBI ini maka orang tua yg semula ingin menyekolahkan anaknya di luar negeri lantas membelokkannya ke sekolah RSBI?
Jika argumen bahwa program RSBI dibuat utk mencegah anak-anak orang kaya bersekolah ke LN maka ini sungguh naïf. Kenapa pemerintah harus membuat program KHUSUS untuk mencegah anak-anak kaya bersekolah di LN? Berapa banyakkah sebenarnya siswa menengah kita yg belajar ke LN dan seberapa urgen masalahnya sehingga harus dibuatkan program khusus utk mencegahnya? Mengapa pemerintah mesti mencegah anak-anak orang kaya tersebut bersekolah ke LN? Apa kepentingan pemerintah (dalam hal ini kementerian pendidikan) dengan mencegah mereka belajar ke LN? Anak-anak pintar (apalagi kaya) dengan mudah bisa mencari pendidikan bermutu DI MANA SAJA. Bagi mereka itu pintu utk masuk ke mana saja selalu terbuka lebar. Mereka tidak butuh sekolah gratis dan bisa bayar sekolah swasta se mahal apa pun. Uang bukan masalah bagi mereka dan pemerintah tidak perlu repot-repot membuatkan sekolah khusus bagi mereka agar tidak perlu belajar ke luar negeri dan justru sebaliknya DORONG mereka utk bersekolah ke swasta dan kalau perlu ke luar negeri. - Program SBI ini di lapangan ternyata menciptakan kesenjangan sosial pada siswa. Program SBI menjadikan sekolah yang mengikutinya menjadi eksklusif dan menciptakan kastanisasi karena hanya bisa dimasuki oleh anak-anak kalangan menengah ke atas. Tingginya pembiayaan yang dikenakan pada orang tua siswa membuat sekolah-sekolah SBI ini tidak dapat dimasuki oleh anak-anak dari kalangan bawah. Akibatnya terjadi kesenjangan sosial di sekolah. Siswa yang belajar di program ini merasa seperti kelompok elit yang berbeda dengan siswa kelas reguler.
- Salah satu kritik terbesar dari masyarakat tentang SBI ini adalah bahwa program ini telah memberi legitimasi kepada sekolah untuk melakukan komersialisasi pendidikan. Pendidikan diperdagangkan justru oleh pemerintah yang seharusnya memberikan pelayanan pendidikan kepada rakyatnya secara gratis dan juga bermutu. Komersialisasi pendidikan ini adalah pengkhianatan terhadap tujuan pendirian bangsa dan negara. Saat ini sekolah-sekolah publik RSBI bahkan telah menjadi lebih swasta dari swasta dalam memungut biaya pada masyarakat. Hampir semua sekolah RSBI menarik dana dari masyarakat dengan biaya tinggi yang sebenarnya sungguh tidak layak mengingat mereka adalah sekolah publik yang semestinya dibiayai sepenuhnya oleh pemerintah dan haram sifatnya menjadi komersial. Saat ini biaya untuk masuk ke sekolah SMA RSBI mencapai Rp. 15.000.000,- untuk biaya masuknya dan Rp. 450.000,- untuk SPP-nya. (panduan Seminar Nasional SBI)
- Salah satu masalah yang muncul dari istilah bertaraf internasional adalah kerancuan dan keganjilan. Sungguh ganjil jika sebuah UU Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) tiba-tiba memunculkan sebuah istilah bertaraf internasional ! Mau dimasukkan ke mana dan dengan konstelasi bagaimana sebuah sistem pendidikan yang bertaraf internasional dalam sebuah Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas), apalagi dianggap sebagai standar tertinggi? Coba bayangkan betapa ganjilnya sebuah UU tentang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) yang justru mengagung-agungkan kurikulum negara asing (OECD).
- Keganjilan dan ambigu lainnya adalah masalah evaluasi. Meski menyandang nama bertaraf internasional tapi siswanya masih harus ikut ujian nasional. Alangkah ganjilnya jika sebuah sekolah yang bertaraf INTERNASIONAL tapi kemudian masih harus mengikuti sebuah UJIAN NASIONAL! Adalah tidak mungkin sekolah harus mempersiapkan siswa untuk mengikuti DUA SISTEM UJIAN yang berbeda (nasional dan internasional) karena itu SANGAT MEMBERATKAN guru dan siswa serta tidak bermanfaat. Selain itu dengan terburu-buru sekolah RSBI/SBI kita lantas mengadopsi sistem ujian Cambridge (CIE) bagi siswa-siswanya agar dapat disebut bertaraf atau berstandar intenasional padahal kurikulum nasional kita tak ada hubungannya dengan sistem tersebut. Coba juga jawab apa sebenarnya urgensi dari ujian Cambridge pada siswa-siswa RSBI/SBI yang tidak ada hubungannya dengan sistem pendidikan nasional kita? Ujian Cambridge juga TIDAK dipersyaratkan bagi siswa yang hendak belajar ke luar negeri . Siswa-siswa kita yang hendka belajar ke luar negeri tidakpernah dipersyaratkan harus memiliki harus lulus ujian Cambridge sehingga mengikuti ujian Cambridge sebenarnya justru memberatkan siswa kita apalagi yang tidak ingin melanjutkan studinya ke luar negeri.
- Kesalahan konseptual (R)SBI adalah terutama pada penekanannya pada segala hal yang bersifat akademik dengan menafikan segala yang non-akademik. Semua keunggulan yang hendak dicapai oleh program SBI ini adalah keunggulan akademik semata dan tak ada lain. Seolah tujuan pendidikan adalah untuk menjadikan siswa untuk menjadi seseoarang yang cerdas akademik belaka. Tak ada dibicarakan tentang keunggulan di bidang Seni, Budaya, dan Olahraga. Padahal paradigma keunggulan akademik adalah pandangan yang sudah sangat kuno. Seolah bertaraf internasional adalah keunggulan akademik padahal justru Seni, Budaya, dan Olahragalah yang akan lebih mampu mengantarkan kita untuk bersaing dan tampil di dunia internasional. Jika kita tanya pada hampir semua orang mengenai apa yang mereka ketahui tentang Negara Argentina maka jawaban yang kita dapatkan mayoritas menyatakan Maradona.! Dan Maradona bukanlah symbol tentang keunggulan akademik samasekali. Di negara lain pemerintah juga menyelenggarakan pendidikan khusus bagi anak-anak yang paling berbakat agar mereka dapat melesatkan potensi mereka tanpa bergantung pada siswa yang lambat. Ada beberapa sekolah publik untuk gifted students di Australia. Meski demikian pembiayaannya tidak dengan menarik iuran pada orang tua. Sekolah tersebut harus kreatif mencari dana untuk membiayai kegiatan-kegiatannya yang padat tersebut.
Satu hal lagi, mereka justru menonjolkan kehebatan kegiatan olahraganya dan bukan capaian akademiknya.
USULAN
- Karena interpretasi dari istilah bertaraf internasional ternyata menimbulkan kerancuan, ambigu serta masalah-masalah yang mendasar dan serius di lapangan maka perlu adanya suatu REINTERPRETASI dan REFORMULASI dari rumusan sekolah bertaraf internasional yang ada selama ini. Usulan rumusan dasar tersebut adalah sbb :
Satuan Pendidikan yang bertaraf Internasional adalah sekolah yang dapat memberikan pelayanan pendidikan berkualitas tinggi kepada siswa-siswa yang memiliki potensi akademik dan non-akademik yang sangat menonjol sehingga siswa-siswa tersebut dapat memiliki bekal pengetahuan, ketrampilan dan sikap pribadi serta kompetensi dan prestasi akademik dan non-akademik yang menonjol dan memiliki kemampuan untuk berkolaborasi secara internasional.
Pelayanan pendidikan yang bertaraf internasional di sini mencakup 8 SNP dan ditambah dengan pelayanan pendidikan tambahan yang akan dapat memunculkan kompetensi terbaik dari siswa agar dapat memiliki daya saing internasional.
Ada tiga komponen penting yang mencakup pengertian bertaraf internasional di sini, yaitu :
a.Pelayanan sekolah yang bermutu tinggi
b.Input siswa yang memiliki potensi akademik dan non-akademik yang sangat menonjol
c.Prestasi akademik dan non-akademik di bidang Seni, Budaya, dan Olahraga serta kemampuan untuk bekerjasama dan berkolaborasi secara internasional dengan lulusan dari mana pun.
Interpretasi ini sesuai dengan amanah Undang-undang yang mewajibkan pemerintah untuk memberi pelayanan bagi anak berkebutuhan khusus. Anak-anak yang memiliki bakat menonjol perlu mendapat pelayanan pendidikan yang khusus pula. Rumusan ini akan memberikan keleluasaan bagi pemerintah dan sekolah untuk merumuskan keunggulan spesifik dari sekolah dalam memberikan pelayanan yang unggul dan sebaik-baiknya bagi siswa-siswa berbakat baik di bidang akademik maupun non-akademik. - Dengan konsep seperti ini maka tidak diperlukan lagi segala macam aksesori dan kosmetik yang tidak perlu pada program ini agar berbau internasional seperti : Standar ISO, Ujian Cambridge, IBO, TOEFL, Sister School, Studi Banding ke luar negeri, kelas ber AC, menggunakan laptop dan proyektor, dll. Sekolah dapat memusatkan perhatiannya pada program-program dan proses pembelajaran yang benar-benar dapat merangsang siswa untuk mengembangkan potensinya secara optimal melalui program-program yang sudah diketahui efektifitasnya. Pendidikan harus benar-benar diarahkan pada proses dan bukan pada alat dan aksesori. India telah memberikan contoh bagaimana menyelenggarakan pendidikan berkualitas dunia dengan fasilitas dan sarpras yang sederhana.
- Dengan meninggalkan program yang tidak substantif seperti ujian Cambridge dan TOEFL maka kerancuan dan kritik tentang sistem pendidikan nasional yang ujiannya mengacu pada sistem lain di luar ujian nasional akan berhenti dengan sendirinya. Sekolah-sekolah publik hanya akan menyelenggarakan ujian yang diamanatkan oleh Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas).
- Dengan konsep yang sederhana, operasional dan terukur seperei ini maka kemungkinan keberhasilan dari program ini akan lebih besar, lebih terukur, dan lebih operasional yang kemudian akan dapat di adopsi oleh sekolah-sekolah lain. Dengan demikian program peningkatan kualitas sekolah ini dapat disebarluaskan ke sekolah-sekolah lain yang mau mengadopsinya. Ia akan dapat menjadi model pengembangan sekolah yang dapat diadopsi dan dikembangkan secara meluas dan tidak hanya berhenti pada sekolah SBI semata.
- Konsep SBI yang lama yang hanya menonjolkan kemampuan akademik siswa semata hendaknya direinterpretasikan ulang dan kemudian haruslah memberikan porsi yang sama besarnya kepada bakat menonjol siswa yang bersifat non-akademik seperti Seni, Budaya, dan Olahraga karena pada hakikatnya dalam kehidupan nyata bakat di bidang non-akademik dan kecerdasan-kecerdasan lain yang tercakup dalam multiple intellegencies justru sangat dibutuhkan dalam kehidupan mereka di dunia nyata kelak. Pengagungan kepada bakat akademik semata menunjukkan ketidakpahaman kita akan dimensi pendidikan itu sendiri yang memang tidaklah semata akademik. Pengembangan potensi akademik semata hanya akan menciptakan siswa yang cerdas akademik semata tapi tidak memiliki kecakapan lain yang justru dibutuhkannya dalam kehidupan nyata kelak.
- Karena sekolah ini adalah sekolah bagi anak-anak dengan bakat yang sangat menonjol maka tuntutan bagi siswanya juga lebih tinggi dibandingkan sekolah reguler. Hanya siswa-siswa yang memiliki bakat, minat, kemampuan, dan kemauan yang menonjol yang bisa mengikuti program ini. Beberapa contoh tuntutan akademik dan non-akademik yang harus dilakukan oleh siswa pada program ini adalah :
- Untuk itu semua bidang studi (kecuali bahasa asing) harus diajarkan dalam bahasa Indonesia yang baku dan standar untuk meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa nasional tersebut. Janganlah lagi kita mengikuti kesalahan yang sama yang dilakukan oleh pemerintah Malaysia yang telah pernah melakukan program PPSMI yang mewajibkan penggunaan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar yang ahirnya justru menurrunkan mutu siswa dan sekolah pada bidang studi yang diajarkan dalam bahasa Inggris tersebut. Dengan dihapuskannya kewajiban menggunakna bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar di kelas maka guru dapat kembali memfokuskan persiapannya pada proses pembelajaran yang efektif dan tidak perlu berjibaku menggunakan bahasa Inggris yang samasekali tidak dikuasainya tersebut. Kita tidak perlu mengikuti kesalahan yang sama telah dilakukan oleh pemerintah Malaysia.
- Untuk meningkatkan kompetensi siswa dalam menggunakan bahasa Inggris sebagai bekal untuk hidup di dunia global maka pelajaran bahasa Inggris mesti ditambah porsinya baik itu jumlah jam belajarnya mau pun efektifitas pembelajarannya. Pembelajarannya juga harus lebih variatif agar dapat mendukung berkembangnya kemampuan siswa dalam 4 ketrampilan berbahasa Inggris yang mencakup : Listening, speaking, Reading dan Writing. Berbagai program dapat sidusun untuk meningkatkan kompetensi siswa ini. Ada banyak program dari lembaga-lembaga internasional yang dapat diadopsi untuk mencapai tujuan ini.
- Untuk menghindari komersialisasi pendidikan maka semua biaya yang ditimbulkan oleh program ini harus ditanggung sepenuhnya oleh pemerintah pusat dan daerah. Ini adalah program yang seharusnya menjadi program kebanggaan pemerintah pusat dan daerah sehingga pembiayaannya memang tidak membebani orang tua siswa. Anak-anak yang berbakat luar biasa sudah selayaknya mendapat bea siswa untuk menunjang perkembangan potensi mereka tersebut. Untuk mendapat tambahan biaya pendidikan maka pemerintah daerah dapat menggalang bantuan dari berbagai perusahaan yang ada di daerahnya melalu program CSR.
- Untuk menjamin keberhasilan program sekolah berkeunggulan tinggi (school for the gifted and talented) ini maka semua guru harus memenuhi kriteria kompetensi yang ditetapkan dan sekolah yang ditetapkan harus melakukan upaya penjaminan kualitas SDM-nya. Untuk itu maka sebenarnya tidak diperlukan guru yang berkualifikasi S-2. Apalagi jika kualifikasi S2 yang dimiliki tidak memiliki korelasi dengan bidang studi yang diajarkan oleh guru tersebut. Saat ini para guru berlomba-lomba mengejar gelar S2 tanpa perduli apakah bidang studi yang ingin dicapainya itu sesuai atau linear dengan bidang studi yang diajarnya di sekolah. Dengan menghapus persyaratan kualifikasi S2 tapi mensyaratkan kompetensi profesional di bidang studi yang diajarkannya (on the job performance) maka kualitas pembelajaran di kelas akan dapat tercapai.
a.Membaca dan menuliskan resensi buku (book discussion and book review) dalam jumlah tertentu, umpamanya tingkatan SD 10 buku, SMP 20 buku, dan SMA 30 buah buku.
b.Memiliki kemampuan berbahasa Inggris pada semua ketrampilan (Speaking, reading, writing and listening) dan harus lulus uji kompetensi berbahasa Inggris yang standarnya akan ditetapkan oleh Kemdiknas
c.Mengikuti kegiatan ekstra kurikuler dan community service yang lebih menonjol dibandingkan sekolah reguler dan dapat mewakili daerah masing-masing untuk kepentingan daerah.
d.Memiliki tingkat disiplin dan dapat menjadi teladan bagi lingkungannya.
e.Dst.
Tabik dan sampai disini dulu. Kalau nanti ada ide lagi baru saya tulis lagi.
Salam
Satria Dharma
Jakarta, 30 Oktober 2010

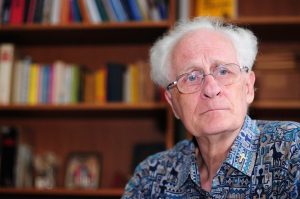


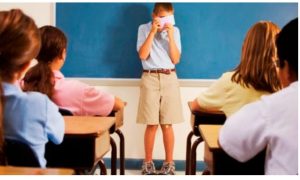
sedih ya jadinya baca tulisan yang sangat bagus dan mencerahkan ini….. terima kasih ya Pa…masih ada aja pejabat dengan pejabat satu atap beda persepsinya ya……maju terus pendidikan Indonesia
Mantab usulannya pak…. Sukses deh kalau gitu sekolah internationalnya.
Apa kabar Pak Satria?
Menarik tulisan kritis Pak Satria tentang kebijakan SBI. Saya ada alternatif pemikiran untuk menanggapi kritikan Pak Satria. Bisa saya cantumkan di blog ini atau dimana?
Salam,
Sopantini
Terima kasih banyak atas kunjungan dan komentarnya Bu Sopantini. Silakan berikan tanggapan Anda di blog ini agar terjadi dialog. Saya tunggu komentarnya.
Tanggapan atas Kritikan Kebijakan SBI
(Sopantini)
Pertama tama saya sampaikan salut atas pemikiran Pak Satria dan kemampuan menuangkan gagasan seputar SBI/RSBI yang bernas yang sudah tertuang di blog ini. Berikut ini urun rembug saya, semoga menjadi alternatif berpikir bagi para pembaca yang budiman.
Saya orang swasta mandiri (bukan orang pemerintah) jadi tidak punya kepentingan untuk membela maupun menjatuhkan pihak manapun. Saya berharap dengan proses ini, terjadi dialog yang berkelanjutan. Namun demikian, saya juga memiliki keterbatasan waktu sehingga belum tentu selalu cepat atau tepat waktu untuk melakukan dialog yang berkelanjutan. Untuk keterbatasan waktu ini, mohon dimaklumi.
Yang tertulis berikut ini (dan mungkin di edisi tanggapan berikutnya) adalah tanggapan saya mengenai kritikan yang ditulis Pak Satria mengenai kebijakan SBI/RSBI. Sekali lagi, secara umum, sumbangan pemikiran Pak Satria merupakan wujut konkret seorang praktisi pendidikan untuk ikut terlibat dalam pembangunan pendidikan di negeri ini. Untuk itu, sewajarnya kita berucap terima-kasih.
Adapun satu tanggapan saya di kesempatan ini adalah menanyakan rujukan apa yang dipakai oleh Pak Satria ketika mengupas kebijakan SBI/RSBI seperti pada butir-butir kritikan tersebut? Pada pembacaan saya…..
Pak Satria tidak mengungkapkan secara jelas, payung apa (bidang ilmu apa) yang dia pakai sebagai landasan berpikir dalam mengupas permasalahan seputar kebijakan SBI/RSBI. Dengan tidak menjelaskan bidang ilmu yang dipakai untuk mengupas masalah kebijakan SBI/RSBI ini, kita menjadi bertanya-tanya rujukan apa yang menjadi dasarnya. Saya tidak bermaksud mengatakan bahwa kritikan-kritikan yang dibuat tidak berbobot tetapi saya merasa perlu mengetahui rujukan yang dipakai yang mendasari kupasan tersebut.
Adanya rujukan (yang sama) akan membuat pembaca bisa dengan jelas menilai bobot dari setiap kritikan yang ditulis. Menurut saya, menyatakan rujukan itu sangat perlu. Tetapi kalau ternyata kita tidak punya rujukan, adalah penting pula untuk kemudian mengatakannya juga. Kenapa? Supaya, persepsi yang terbentuk di benak pembaca tidak ‘salah’. Sudahkah ada persepsi ‘salah’ (yang terbentuk)? Sudah dan sering. Tetapi dalam hal ini, bukan persepsi tentang Pak Satria. Lalu tentang siapa? Misalnya, persepsi yang dibentuk masyarakat tentang seorang yang katanya hebat karena dia punya status (pejabat, harta, ketenaran dll.) Bahkan persepsi yang semacam ini juga terbentuk di kalangan masyarakat kita yang terdidik sekalipun.
Apa contohnya sebuah persepsi ‘salah’ itu? Menurut saya adalah salah persepsi, jika karena kita tidak menyatakan rujukan, kritik kita diterima sebagai sebuah kebenaran oleh pembaca karena hal-hal lain, misalnya karena ’embel-embel’ yang melekat di diri kita. Dalam hal ini saya juga tidak berpikir kalau Pak Satria menginginkan bahwa apa yang dia kupas tentang SBI/RSBI tersebut merupakan ‘kebenaran’? Semoga demikian adanya yang ada di benak Pak Satria. Mungkin dari sekian banyak yang membaca tulisan Pak Satria, saya termasuk sedikit dari kelompok yang menanyakan apa rujukan yang dipakai. Saya tidak terkejut jika kebanyakan pembaca larut dalam kesan kehebatan menikmati kupasan kritikan yang dibuat tetapi lupa menanyakan hebatnya berdasarkan apa.
Menurut saya, menanyakan apa dasar/rujukan sesuatu itu penting, terutama di tengah-tengah masyarakat kita yang cukup patriakis dan mudah silau (baik oleh kedudukan, jabatan, dan simbol-simbol lain) yang belum tentu merupakan representasi yang tepat orang yang memiliki (jabatan, kedudukan, status, dan simbol-simbol) yang dimaksud. Saya agak risau dengan gejala mudah kagum dan lupa menanyakan dasar rujukan yang saya amati. Kalau memang kita bukan ahlinya cukup beralasan kalau kita risau dan merasa kuatir jangan-jangan nanti, kita dianggap ahli-nya’, padahal sebetulnya kita memiliki keahlian dibidang tertentu saja dan bukan dibidang yang sedang kita kupas pada saat itu. Penting untuk saya katakan disini bahwa saya tidak bermaksud menyindir, tetapi menyampaikan pengamatan pribadi, yang tentunya bisa di-dialogkan. Akan menarik untuk mendengar dari sidang pembaca pengamatan mereka terhadap satu hal yang saya sampaikan disini.
Kembali ke tanggapan saya tentang tulisan Pak Satria.
Sejauh yang saya ketahui, permasalahan seputar kebijakan SBI/RSBI (dan kebijakan pendidikan lainnya) berikut kritikan-kritikan yang Pak Satria buat, bisa dikategorikan masuk di ranah bidang ilmu sosial, yaitu ilmu kebijakan (policy studies), dimana kebijakan pendidikan (educational policy) merupakan sub-bidangnya. Dibidang ini dikenal dua tataran, yaitu tataran kebijakan (policy) dan tataran penerapan (practice). Bidang ini sepertinya belum masuk bidang studi di universitas di Indonesian. Ada yang tahu universitas mana yang menawarkan/menjadikan bidang studi ini dalam paket mereka?
Karena tiadanya tulisan yang menjelaskan rujukan yang dimaksud, kupasan yang ada terbaca tumpang tindih dan campur aduk. Bagaimana campur aduk dan tumpang tindihnya bisa kita bahas di lain waktu.
Sekian dulu semoga tanggapan diatas bisa memberikan alternatif berpikir termasuk bagi penulis dan sidang pembaca lain yang budiman.
Pada kesempatan ini pula, saya ucapkan salam kenal bagi para sidang pembaca lainnya. Tetaplah semangat untuk membangun dialog.
masalah pendidikan
kalao SBI dan RSBI sebagai sebuah proses memajukan pendidikan indonesia saya sepakat keberadaannya. namun jika dengan status itu sekolah lebih mengarah agar dapat memungut dana dari orang tua siswa saya tidak sepakat.
lantas , bagaimana menurut sampeyan mas, untuk memajukan pendidikan kita. Saya setuju karena kita memang terlalu suka nyontoh orang n negara lin , padahal kita udah punya akar pendidikan seperti NU, Muhamadiyah, pesantren, taman siswa dll. Merekalah yang punya hasil jelas yakni pahlawan bangsa. saya lama2 sedih juga lho lihat carut marutnya pendidkan kita. lantas apa yg harus sy perbuat ? hik 13x. salam kami. mohon di tanggapi ya mas. jazakumulloh
Salam Pak Satria
Satu pemerhatian yang menyeluruh dan pandangang kritis yang tepat sekali. Saya secra peribadi tertarik dengan point nombor 10. Sememangnya tanggung jwab yang lebih besar dan amat terpenting adalah dibahu pendidik dan pakar itu sendiri. NO DOUBT ABOUT THAT.
mantab banget pak tulisannya,bisa buat inspirasi skripsi saya…terimakasih banyak…
SBI atau RSBI, apa pun namanya itu tidak usah dulu dilihat secara skeptis. Tujuannya utamanya pastilah sangat mulia, yaitu untuk meningkatkan mutu, meningkatkan daya saing, dan menyiapkan anak-anak dalam menghadapi perubahan abad ke 21. Jika pelaksanaannya terjadi seperti yang kita alami sekarang bukan berarti niat di muka yang salah, tetapi pengelolaannya yang belum baik. Pengelolaan yang belum baik ini bisa disebabkan oleh kapasitas dan mutu pengelolanya (pengambil kebijakan dan pembina pada tingkat kementerian pendidikan, dinas2 pendidikan, kepala sekolah2, dan guru2) belum memadai/masih rendah. Namun kemampuan itu bisa ditingkatkan jika mau belajar (eager to learn) tinggi.
Sejak reformasi (lebih dari sepuluh tahun terakhir) persoalan mutu/kualitas kepala sekolah dan guru paling sering diabaikan. Padahal dari banyak studi di banyak negara, gabungan kemampuan kepala sekolah dan guru bisa menentukan keberhasilan pembelajaran anak mencapai 70 persen. Mutu guru dan kepala sekolah sejak 15 tahun terakhir grafiknya terlihat menurun, hal diindikasikan dari data ujian PISA dan TIMSS. Jika kita analisis secara detail, laporan teknis dari PISA dan TIMSS, maka akan kita akan sampai pada kesimpulan bahwa mutu pembelajaran yang dilakukan guru2 dibalik ruang kelas tertutup itu, yang selama ini tidak pernah dipantau (dilakukan supervisi dan dampingan) oleh kepala sekolah dan pengawas, masih sangat rendah dan sangat memprihatinkan. Guru2 hanya mengajarkan pengetahuan/kemampuan deklaratif atau rote-learning kepada anak2 (siswa2) kita. Pembelajaran yang membutuhkan complex thinking dikesampingkan. Data TIMSS dan PISA menunjukkan 70 persen anak2 Indonesia pada bidang sains dan matematika hanya mampu menjawab soal2 yang mengukur kemampuan knowledge dan comprehension; dan hanya 20 persen yang hanya mampu menjawab soal2 yang mengukur kemampuan aplication, dan lebih sedikit lagi anak2 kita yang bisa memecahkan soal2 yang menuntut kemampuan analitik dan problem solving. Bandingkan anak2 Thailand, 70 persen dari mereka sudah mampu menjawab soal2 yang menuntut kemampuan application, analitic, dan problem solving.
Jadi jika kita mengacu pada kurikulum negara OECD bukan berarti hanya penggunaan bahasa Inggris dalam pembelajaran, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengolah praktek pembelajaran yang mampu meningkatkan kemampuan berpikir (thinking skills) dan creativitas, communication skills, collaboraton, dan kemampuan mentransformasikannnya ke dalam kehidupan nyata (authentic teaching and assessment). Di sekolah-sekolah yang menggunakan kurikulum nasional (ktsp) kemampuan di muka tidak diolah secara maksimal karena ujian nasional kita sangat tidak sentisif terhadap proses pembelajaran di kelas. Guru2 hanya mangajar sesuai dengan tuntutan UN yang sudah sangat minimal itu. Jika keadaan ini dibiarkan, bangsa ini akan mengalami degradasi pada banyak sektor kehidupan, ekonomi, demokrasi, sosial-budaya, keagamaan. Tanda2 kearah itu sudah nampak didepan mata. Masyarakat kita kini tumbuh menjadi bangsa yang sudah sangat korup (mereka yang korup itu sudah tidak yakin lagi bahwa kehidupan setiap individu sudah dijamin oleh Tuhan Yanga Maha Esa rejekinya), masyarakat menjadi sangat pemarah dan anarkis (tawuran bulliying, perampokan, penipuan, pencurian sudah menjadi pemandangan kesaharian kita), kemiskinan dan pengangguran semakin melonjak, budaya sopan santun dan pendahulukan kepentingan umum sudah hampir hilang. Lihatlah bagaimana corak lalu lintas kita, sembraut, mau menang sendiri, dst.
Menurut saya, kita selaku praktisi pendidikan baik itu kepala sekolah, guru, manajemen sekolah dan pemerintahan ikut bertanggung jawab memproduksi kualitas masyarakat seperti yang saya gambarkan di muka. Guru2 dan dosen2 harus diminta pertanggung jawabannya jika meluluskan anak2 yang kualitasnya rendah sehingga mereka mengalami kesulitan mencari pekerjaan dan membangun kehidupan yang lebih baik ke depan. Dosen IKIP (Pendidikan Guru) harus bertanggung jawab bila meluluskan guru2 yang bermutu rendah dan tidak layak mengajar. IKIP harusnya merekrut dan mendidik calon guru dengan kualitas tinggi. Itu yang dilakukan oleh negara2 OECD, karenanya kita tidak usah malu belajar dari mereka. Lihat kualitas pembelajaran, penilaian yang sudah mereka kerjakan dan terus kembangkan. Datanglah ke sekolah Ghandi School, Tiara Bangsa, Global School, dan sekolah2 lain yang sudah menerapkan kurikulum IB atau Cambridge IGCSE dan A Level. Anda akan banyak belajar dari sana. Jangan bandingkan biayanya, tapi lihatlah bagaimana mereka mengelola pembelajaran, penilaian, membangun interaksi guru-siswa (personalized learning), membangun rasa percaya diri pada siswa, kemampuan risk-taking anak2, toleransi, respect, dan lainnya. Sekolah2 negeri dan swasta kita meskipun sudah diberi lebel RSBI atau SBI belum memperhatikan kualitas semacam itu. Kita harus mau belajar jika tidak mau dikutuk oleh anak2 murid kita nantinya, karena kita (guru2) telah gagal menyiapkan mereka untuk bisa hidup di abad ke 21 ini. Ungkapan klasik China, menyebutkan : “Jangan didik anak2 sekarang seperti kamu dididik dahulu, karena mereka adalah milik generasi mendatang” yang problem dan tantangannya sudah sangat jauh berbeda dari yang kita hadapi/alami sekarang.
Semoga bisa mencerahkan.
Wassalam,
Syamsir Alam,
Penggiat, CIE- Indonesia Belajar
Bagus sekali pa……semoga yang diatas pada mendengar masukan dan usulannya…. dan yg terpenting realiasasi nya…..
apalah arti sebuah nama, tif yang baik untuk meningkatkan pendidikan di negeri kita ini cukup mudah, bina aqidah,moral dan akhlak. perbanyak ilmu. dan mari kita tunjukkan jati diri kita tidak usah ikut-ikutan berbaha asing di dalam KANDANG KITA SENDIRI, tidak usah meniru kepada negara-negara maju(BARAT), bukan level kita, bukan panutan kita orang yahudi dan nasrani.kita negara beragama, dengan cita-cita panca sila.dak usah neko-neko KITA HARUS PUNYA PRINSIP.
jangan sampe kita kena stroke!
Setuju banget dgn Paparan Pak Satria…blm lagi beban psikologi/beban modal guru rsbi yg cenderung membiayai peningkatan mutu dari kocek sendiri(yg sedikit);beban administrasi birokrasi (pangkat/sertifikasi dll) yg kecenderungan juga dgn modal Rp.Dengan demikian sangatlah tdk adil bila siapapun selalu mendiskreditkan kwalitas pendidikan pada guru “tidak berkualitas” semoga bangsa ini tidak grusa grusu dlm membuat kebijakan serta yakin bahwa bangsa ini mampu membangun anak negeri dgn rasa Percaya Diri .
Semoga pemerintah mau mendengar dan segera mengevaluasi pelaksanaan RSBI ini. Sebagai guru yang melaksnakan program ini, saya berharap ada perbaikan konsep yg telah dibuat oleh IGI.
salam
Omjay
Sebuah usulan yang cerdas, pengalaman sy mengajar di RSBI: pertama, RSBI di daerah membuka peluang perbedaan jurang yang dalam kesejahteraan antara guru biasa dengan guru yang menjabat sbg kepsek-wakasek-staf; kedua, penggunaan bahasa inggris yang dipaksakan bukan menambah pintar siswa malah menambah semakin bingung pemahaman thd subtsansi materi yang disampaikan; ketiga, terbuka lebar peluang kecurangan penggunaan anggaran RSBI. terima kasih
Saya bukan orang pemerintah, bukan pula siswa RSBI, bukan guru, dan bukan pihak yang berkepentingan dalam pro kontra ini. Saya ingin menyampaikan bahwa tulisan Pak Satria sama sekali tidak melibatkan data dan hanya berbentuk opini dimana opini tanpa data itu tingkat kebenarannya patut dipertanyakan. Apa betul semua RSBI seperti yg Pak Satria sebutkan? Berapa banyak yg seperti itu? Berapa ratio RSBI yg berhasil vs yg gagal? Apa indikator keberhasilan yg Pak Satria sebutkan itu sudah valid? Intinya, mana datanya? Semua orang bisa berbicara dan berpendapat, dan pendapat orang besar dan hebat seperti Pak Satria pun bisa saja salah, karena kita semua sama-sama manusia. Bila Pak Satria mampu menyajikan data, maka akan lebih baik karena kebenaran pendapat Pak Satria adalah empiris, bukan benar karena Pak Satria adalah orang hebat yg ‘dianggap’ benar.
Sebetulnya pertanyaan ini seharusnya ditujukan kepada Kemdiknas dan pra konsultannya yang membuat sebuah program yang bernama (R)SBI dengan biaya trilyunan tapi TANPA menggunakan rujukan akademik dan juga TANPA menggunakan data dan statistik untuk mendukung konsep dan program RSBI tersebut. Anehnya, justru saya yang diminta untuk memberikan data dan statistik! 🙂
Apa yang disusun oleh Kemdiknas dengan Panduan Pelaksanaan Program SBI-nya hanyalah berupa asumsi-asumsi dan tidak menggunakan rujukan akademik. Merekalah yang seharusnya ditanyai mengapa membuat program besar tanpa menggunakna kajian akademik.
Apakah saya tidak punya data…?!
Check this out. https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=explorer&chrome=true&srcid=0B-pXbcM8cTV_ZTlkODEyMmYtYTc1OC00N2ZjLWFjNGUtODBiNWNiN2I2MDFj&hl=en
Paparan ini saya sampaikan pada Simposium ayng diadakan oleh British Council pada tanggal 9-10 Maret 2011 di Hotel Atlet Century.
Ini juga untuk menjawab Bu Sopantini. Kemdiknas meluncurkan program ini dengan konsep yang hanya berupa asumsi dan bukan berdasarkan kajian akademik. Saya punya kajian akademik untuk membantah semua asumsi tersebut. Kapan saja saya dipertemukan dengan snang hati akan saya tunjukkan kajiannya.
bagus dan salut atas pemikiran pa satria tentang RSBI memang sudah saat IGI memberikan pemikiran dan pencerahan bagi dunia penddikan kita
assalaamu’alaikum sir..
i agree with your statement..i hope education in indonesia will be Filnlandia applayed..
Siapakah yang pernah menjadi siswa asing di luar negeri semasa SD hingga SMA, juga pernah berkecimpung di Depdikas periode 15 tahun terakhir ini, dan juga pernah menjadi pengajar sekolah Internasional baik di Indonesia maupun di luar negeri?
Saya akan berdiskusi panjang mengenai topik ini dengannya.
Saya yang akan mengkontak Anda untuk berbicara lebih mendetil untuk membuat perbaikan ke depan.
Thx
ibu @nina: sy tunggu kontaknya. sy salah satu pengajar di sekolah internasional di bandung dan juga pengajar di PTN n PTS yg berbahasa pengantar bhs inggris. ditunggu lho..makasih…
asik bget nih bwt referensi
Senang sekali membaca dan mengetahui isi tulsan-tulisan anda semua. Benar-benar menambah wawasan saya tentang pendidikan di Indonesia. Btw untuk ibu Nina S dan Rakean Sunu : sudahkah anda berdiskusi ? Kalau sudah, maukah anda share ke kami di sini ? Saya penasaran ingin tau. Terimakasih.
artikel ini sangat bermanfaat, terutama bagi para pengelola lembaga pendidikan. Teruslah berbagi ilmu.. Semoga Anda selalu sukses.
Mantab baca ini, sejak usulan no satu sampai ke tujuh saya membaca masih dari sudut pandang siswanya, bahkan ke delapan dan kesembilan. Akhirnya ke sepuluh keluar juga yang saya tunggu-tunggu. Prespektif dari kemampuan gurunya, menurut saya ini yang banyak dilupakan.
Hebat.. ini tulisan yang hebat, kenapa gak dikorankan pak?
salam
Ardlian
Pak Satria….tulisan dan ulasan yang sangat baik dan informatif bagi pembaca. Mohon bantuannya data atau informasi dari pak Satria, khusus untuk kondisi guru RSBI di Jogja. Saya ingin meneliti tentang “Komparasi Self-Efficacy Guru Sekolah Dasar Sekolah Nasional (SDSN) dan RSBI”. Boleh jadi hasil penelitian nanti, akan saya bagikan pada pak, dan siapa saja yg membutuhkannnya. Kalau ada informasi tentang guru RSBI, khusunya SD se_DIY, mohon kesediaan pak Satrio, mengiirim via emali saya: kristoforusbili@yahoo.co.id. JIka pak Sastiro masih perkenan kita share nomor HP. (No hp saya: 081 339 834 460).
Pak Satria .tulisan dan ulasan yang sangat baik dan informatif bagi pembaca. Mohon bantuan data atau informasi dari pak Satria, khusus untuk kondisi guru RSBI di DIY. Saya ingin meneliti tentang Komparasi Self-Efficacy Guru Sekolah Dasar Sekolah Nasional (SDSN) dan RSBI. Boleh jadi hasil penelitian nanti, akan saya share pada pak, dan siapa saja yg membutuhkannnya. Kami meneliti dalam team (masih ada 4 teman. Aspek lain yg diteliti adalah budaya, ekspektasi orang tua, kesiapan sekolah, dan prestasi) Kalau ada informasi tentang guru RSBI, khusunya SD se_DIY, mohon kesediaan pak Satrio, mengiirim via emali saya: kristoforusbili@yahoo.co.id. JIka pak Sastiro masih perkenan kita share nomor HP. (No hp saya: 081 339 834 460). Kalau ada masukan konstruktif untuk penelitian ini, sangat baik. Terima kasih sebelumnya dan salam maju terus….!
Mohon maaf, saya tidak punya data seperti yang dimaksud. Tapi masalah RSBI telah dibahas banyak orang untuk menjadi thesis/disertasi mereka, salah satunya adalah Agustina Kustulasari pengajar Universitas Sanata Darma yang bisa Anda hubungi di agkustulasari@yahoo.com
Semoga membantu.